Jelek-jelek begini, waktu kuliah dulu saya pernah menang lomba karya tulis se-DKI Jakarta, lho! Saya khusus membahas mengenai ecotourism. Mengapa saya jadi menyombong teringat kembali mengenai karya tulis ini? Tidak lain dan tidak bukan, karena ribut-ribut di linimasa saya: perihal voting Pulau Komodo untuk program New 7 Wonders yang kontroversial itu. Sebagai orang Indonesia, kita tentu bangga jika Pulau Komodo dinobatkan menjadi salah satu dari 7 Keajaiban Dunia. Mungkin ini juga yang membuat voting SMS untuk Pulau Komodo masih deras mengalir. Tetapi, pertanyaan selanjutnya adalah: untuk apa?
Apa manfaat memenangkan New 7 Wonders ini bagi Pulau Komodo, penduduk lokal di Pulau Komodo, oleh penduduk lokal di Pulau Komodo, maupun para komodo itu sendiri? Jika jawabannya adalah: semakin banyaknya turis lokal maupun asing yang datang ke Pulau Komodo, pertanyaan saya berikutnya: apakah banjirnya turis lokal maupun asing berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat maupun konservasi di daerah wisata?
Idealnya demikian, sementara pada kenyataannya… sama sekali tidak.
Lihat saja Bali dengan segala permasalahannya kini. Saya ingat, pertama kali saya datang ke Pantai Dreamland, pantai itu baru dibuka dan masih sepi. Saya bisa merasakan keindahannya. Terpesona dengan pasirnya, lautnya… cantik! Tahun lalu saya kembali ke Dreamland untuk mereguk keindahan itu. Apa yang saya temukan? Pantai penuh sesak dengan manusia, penuh sampah, dan berbau.
Sedih? Tentu. Kecewa? Pasti.
Tetapi ini adalah masalah klasik di berbagai kawasan wisata di Indonesia. Baru-baru ini, UNESCO yang sudah menobatkan Borobudur sebagai warisan budaya dunia pun mengancam akan mencoret candi tersebut dari daftar mereka, karena kebersihan candi yang sangat memprihatinkan: mulai dari kompleks candi yang sangat kotor dan tidak terawat; sampai bau pesing yang menyengat. Jika Borobudur—yang sudah masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO saja—berakhir menyedihkan seperti ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa memenangkan New 7 Wonders akan membantu konservasi komodo dan lingkungan sekitar Pulau Komodo?
Untuk saya, yang menjadi masalah adalah: kita terlalu banyak memusatkan perhatian untuk menarik turis datang ke Indonesia, tetapi kurang memberikan perhatian bagi kesejahteraan penduduk lokal maupun konservasi di daerah wisata. Saking sibuknya beraktivitas ‘di luar’, kita sampai lupa melihat ‘ke dalam’.
Bagaimana kita bisa mengharapkan penduduk di daerah wisata menjaga dan merawat lingkungan sekitarnya jika mereka sendiri masih tidak sejahtera dan terdesak secara ekonomi? Bagaimana kita bisa mengharapkan mereka ikut dalam kegiatan konservasi jika merasa sendiri tidak merasakan dampak pariwisata bagi kesejahteraan mereka? Bagaimana kita bisa mengharapkan penduduk lokal menjadi ‘jagawana’ di daerah mereka, jika mereka sendiri masih sulit perekonomiannya?
Karenanya, saya kemudian sangat mengerti, ketika—seperti yang dikatakan Wahyuana Wardoyo: jika kita ingin menolong komodo dan Pulau Komodo, kita juga harus menolong penduduk lokal Komodo agar mereka sejahtera.
Ecotourism—atau ekowisata, sebenarnya bukan konsep yang baru. Ekowisata diartikan sebagai: “Perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke daerah alami, yang ditujukan untuk konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal”. Jika wisata alam atau “nature-based tourism” hanya mendeskripsikan perjalanan wisata ke daerah alami, ekowisata secara spesifik ditujukan juga untuk mendatangkan keuntungan bagi komunitas/penduduk lokal dan daerah tujuan wisata tersebut. Keuntungan ini bisa dalam bentuk konservasi lingkungan atau budaya, maupun keuntungan ekonomis.
Ada enam prinsip utama dalam ekowisata:
- Meminimalkan dampak buruk dari pariwisata. Dampak buruk ini justru yang seringkali kita lihat. Bahwa pariwisata justru membawa lebih banyak sampah, hotel-hotel beton yang justru merusak keindahan alam sekitar, membawa masyarakat pendatang yang bekerja di sektor-sektor pariwisata sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat/penduduk lokal, lunturnya budaya serta tradisi lokal yang tergerus oleh wisatawan asing, dan lain sebagainya.
- Membangun kesadaran akan pentingnya menghargai alam dan budaya. Mari kita iseng-iseng bertanya, ada berapa sekolah sih, di Indonesia yang mewajibkan siswanya belajar menarikan satu tarian daerah, menyanyikan satu lagu daerah, dan memainkan satu alat musik daerah di tempat sekolah tersebut berada? Atau ada berapa anak SD yang mengetahui apa-apa saja kekayaan alam atau kekayaan budaya yang ada di daerah tempat tinggal mereka? Bagaimana kalau yang mempelajari budaya-budaya ini dengan serius justru orang-orang dari luar negeri? Bayangkan, misalnya, jika suatu hari nanti ada pakar gamelan Jawa yang berasal Amerika… padahal gamelannya sendiri ada di sini, orang-orang yang memainkan dan mengambil tempat dalam sejarahnya juga ada di sini.
- Memberikan pengalaman yang menyenangkan dan positif bagi pengunjung maupun penduduk di daerah tujuan wisata. Ketika banyak penduduk lokal yang agresif memaksa turis-turis membeli cinderamata, menipu mereka dengan pura-pura berbaik hati menjadi ‘tour guide‘ gratisan tetapi lalu meminta bayaran mahal setelah selesai mengantar berkeliling—atau bermunculannya lokalisasi di daerah-daerah yang ramai oleh turis… bayangkan pengalaman macam apa yang akan kita rasakan ketika berwisata ke daerah-daerah ini. Di sisi lain, bayangkan perasaan kita jika kita adalah penduduk lokal, tetapi lahan dan tempat usaha kita “digusur” oleh kehadiran hotel-hotel, bar, restoran, serta jasa pariwisata asing—yang justru mempekerjakan atau mendatangkan orang-orang dari luar daerah untuk bekerja di sana.
- Menyediakan keuntungan finansial yang bisa langsung dirasakan untuk konservasi. Ini adalah satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Dalam ekowisata, keuntungan dari pariwisata harus bisa dirasakan dan dialokasikan juga untuk konservasi lingkungan sekitar. Berkaca kepada Pulau Komodo, beberapa kawan mengatakan bahwa pulau tersebut bukannya kekurangan wisatawan, tetapi justru terlalu penuh dengan wisatawan. Ini mendatangkan masalah untuk konservasi, dan tentunya mengganggu penduduk lokal. Bayangkan kalau rumah kita kedatangan tamu sampai penuh sesak. Pasti rasanya tidak nyaman, kan? Pemikiran nakal pun mampir di benak saya: bagaimana jika Pulau Komodo menjadi pulau yang sedemikian alami dan ‘prestisius’, sedemikian dijaga konservasinya, sehingga ada batas maksimum turis yang bisa singgah di pulau (akan ada ijin khusus yang diberikan bagi para peneliti). Jika batas maksimum ini sudah terpenuhi dan pulau memang sudah ‘penuh’, turis lain harus berada dalam daftar tunggu atau waiting list. Semacam principle of scarcity. How cool is that!
- Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat/penduduk lokal. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Pernah pergi ke suatu daerah wisata dan melihat rumah-rumah penduduk atau anak-anak yang berkeliaran di sekitarnya? Bagaimana keadaan mereka? Sejahtera atau tidak? Jika tidak, bisakah kita seratus persen menyalahkan mereka kalau mereka kemudian tak peduli terhadap keberlangsungan pariwisata di daerah tersebut?
- Meningkatkan sensitivitas terhadap keadaan politik, lingkungan, dan sosial di negara tujuan wisata.
Bayangkan jika Indonesia, dengan keindahan alam, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budayanya yang luar biasa, mengedepankan ekowisata dalam keseluruhan program pariwisatanya!
Saya bukan pakar ekowisata—saya hanya gemar berwisata. Tulisan saya di atas, juga mungkin banyak salah-salahnya. Tetapi pepatah Minang ini mungkin ada benarnya: anjuik labu dek manyauak, hilang kabau dek kubalo. Atau artinya kurang lebih: karena mengutamakan urusan yang kurang penting, yang lebih penting menjadi tertinggal karenanya.
Saya tak ingin ini menjadi perdebatan telur atau ayam. Mana yang harus didahulukan: membenahi pariwisata di dalam atau mempromosikannya ke luar? Menurut saya, keduanya penting. Hanya saja, dengan gempuran kampanye dan iklan untuk New 7 Wonders Pulau Komodo yang luar biasa gencarnya itu, perasaan saya mengatakan bahwa kita terlalu sibuk mempromosikan pariwisata kita ke luar tetapi kurang membenahinya di dalam.
Please correct me if I’m wrong.
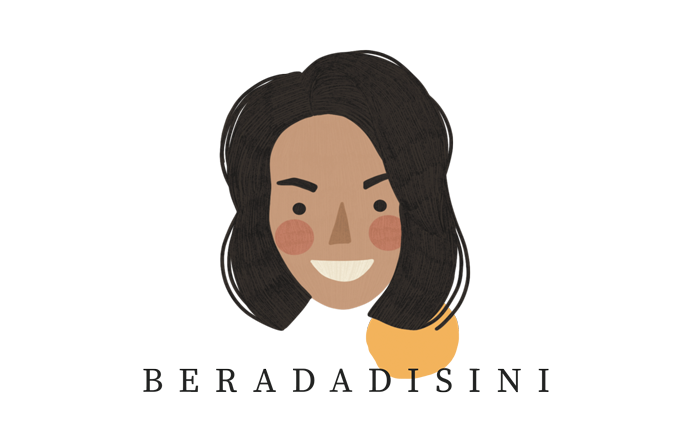







9 Responses
Nah!
Dulu, tahun 2008, saya pernah ikut salah satu acara dengan topik pariwisata. Fam Trip Journalist. Diantara puluhan yang ikut, saya dan teman saya adalah blogger saja. Dan, disana saya (kami) berkesempatan mengunjungi beberapa tempat di Jogjakarta. Peserta lain — yang tentu saja adalah jurnalis — dan beberapa pihak yang diharapkan akan menyebarluaskan pengalaman mereka mengunjungi tempat wisata tersebut cukup antusias. Mengenai hasilnya katakanlah satu atau dua tahun setelahnya, saya tidak tahu.
Yang saya tahu, euforia itu ada, tapi lenyap entah kemana. Yang saya pribadi tangkap untuk hal yang mungkin dalam skala “kecil” ini, adalah bahwa banyak yang mengedepankan “yang penting datang dulu”. Tapi, bagaimana dengan “setelah mereka datang, trus apa?”.
“Jumlah wisatawan asing tiap tahun bertambah”. By numbers, ini prestasi. Mirip yang dirimu sampaikan tadi, apakah ada dampak ekonomi/sosial disana yang cukup signifikan? Entah juga.
Orang berbondong-bondong ke Pulau Komodo (Indonesia), boleh banget. Membangkitkan pariwisata? Bagus juga. Tapi experience ketika dan setelah mengunjunginya ini kayaknya bukan jadi urusan yang “mendatangkan” yak?
Eh, kok jadi panjang ya… Saya dukung “Daging untuk Komodo” saja dehhh…
Hihihi, bisa panjang kalo ngomongin ini, ya. Seru soalnya 🙂 Betul banget, aku rasa saat ini kita sudah cukup berhasil mendatangkan wisatawan, tapi justru masih kurang perhatiannya ke dalam: bagaimana membentuk manajemen dan sistem pariwisata yang menguntungkan konservasi maupun masyarakat lokal, sehingga daerah wisata tidak hanya dieksploitasi lalu ditinggalkan, tetapi bisa terus dilestarikan. Sama saja ya, seperti daerah tambang, setelah digali lalu ditinggalkan tandus…
Di daerah dimana saya tinggal, kabupaten gunungkidul, ada banyak tempat potensial untuk dijadikan wisata minat khusus.
Muncul permasalahan: Pemda tidak cukup mampu untuk mengembangkan semua potensi pariwisata itu. Bila pengelolaan tempat/petensi wisata itu diserahkan kepada kelompok masyarakat seperti desa/karangtaruna dan lain lain, perkembangan dan konsep wisata tidak cukup bagus. Tapi bila diserahkan pada swasta, kemudian apa kemudian yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang daerahnya dikembangkan sebagai obyek wisata 🙁
Kira-kira gimana, ya. Apakah bisa berpartner dengan LSM/NGO untuk memberdayakan masyarakat lokal dan membangun sistem ekowisata yang baik, ya? Begitu sistem sudah berjalan dengan baik, lalu diserahkan kepada masyarakat lokal, lalu dipantau pengelolaannya bersama. Atau jika bermitra dengan pihak swasta, harus dilihat klausul perjanjiannya, misalnya pembagian keuntungan dan kesepakatan untuk menyerap, melatih, dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Banyak yang bisa didiskusikan. Mungkin perlu bikin Obsat soal ini 🙂
@Jarwadi – pantainya di Gunung Kidul iki seksi tenan dengan tebing2 aduhai….
hihi… 😀 oh yo… ditempatku ya gitu mbak, pada buka tambang batubara, selesai ditinggal… yaa beberapa tahun lagi jadi wisata bekas tambang mungkin… *OOT* *ditoyor mbak hanny*
bikin wisata hantu :’D
Eh tapi bukankah pulau Komodo itu sangat unik dan satu2nya di dunia yang menyimpan Komodo?
Jadi, saya rasa, tak mendapatkan tempat di New7Wonders pun tak masalah, karena otomatis jika penduduk dunia mau melihat naga terakhir yang masih hidup di bumi, tentu mereka akan datang ke Indonesia. 😀
Tinggal bagaimana caranya pemerintah dan segala pihak terkait rajin mempromosikan Pulau Komodo ke event2 wisata luar negeri. Juga jangan lupa, infrastruktur penunjang di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk transport dari dan ke Pulau Komodo, harus ada. 🙂
Bener banget. Tanpa harus teriak-teriak ke luar semua orang sudah akan datang dengan sendirinya kok 🙂 Yang darurat itu bagaimana di dalam kita melakukan upaya konservasi dan peningkatan kesejahteraan penduduk lokal, sehingga dalam 10 tahun ke depan, Pulau Komodo masih lestari: dengan komodo yang sehat dan penduduk lokal yang sejahtera juga 🙂
Mengingat komodo di dunia hanya ada di Indonesia, kalaupun tak terpilih menjadi New7Wonders menurut saya tak masalah. Karena yang namanya tempat wisata akan selalu ada pengunjungnya.