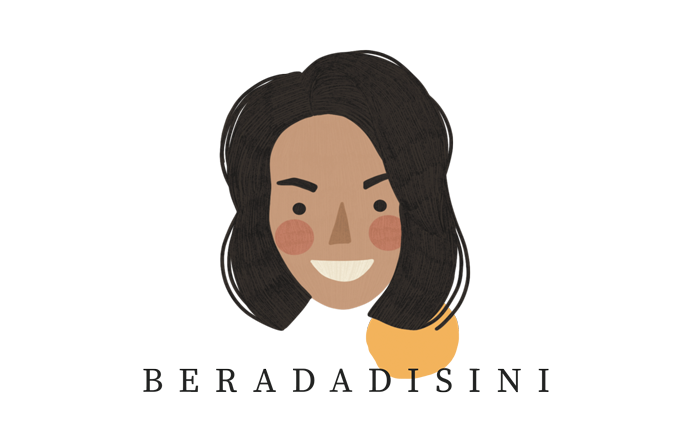We build a bridge of hope from memories. It stretches from here to there—connecting you and me, the structure’s as still as our faith.
Ada beberapa jembatan di Sevilla, yang dibangun menjelang La Seville de la Exposición Universal de 1992. Yang paling terkenal di antaranya adalah Quinto Centenario (mereka bilang banyak kecelakaan yang terjadi di sini), juga jembatan Barqueta dan Alamillo—yang dirancang oleh arsitek kenamaan, Santiago Calatrava. Jembatan-jembatan itu mengingatkanku pada jarak di antara kita. Jarak yang terentang di antara dua hati. Mereka memberikan harapan—jembatan-jembatan itu, seperti mengatakan bahwa jarak selalu bisa diseberangi.
“Sevilla, good! Good! Dance! Flamenco! Very good! Barcelona, flamenco, not good!” kata Salvador bersemangat. Dengan bahasa Inggris yang patah-patah, Salva—demikian ia biasa dipanggil, memperagakan tarian flamenco di atas trotoar yang ramai sebelum menutup pintu taksinya.
Tetapi aku tidak menonton flamenco selama berada di Sevilla, juga tidak mengunjungi Plaza de Toros yang terkenal itu (kamu tahu, kan, aku tak terlalu suka membayangkan ratusan banteng yang sudah mati di arena di dalam sana itu, dalam sebuah pertarungan yang menurutku tak seimbang). Aku menghabiskan dua hari di Sevilla untuk pergi ke kebun raya,
mencelupkan churros ke dalam cokelat,
lalu berjalan-jalan berkeliling kota ketika semua orang tengah siesta. Rasanya seperti berjalan-jalan di kota mati, tanpa penghuni.
Matahari di bagian selatan Spanyol menyorot panas—merambat pelan dari dataran sepanjang sungai Guadalquivir yang melintasi kota dari Utara ke Selatan. Kulitku mulai terasa perih. Sunglasses-ku berembun. Tapi tak mengapa. Aku merasa puas karena bisa memotret dengan bebas: rumah-rumah, gang, gereja, jalanan, juga atap-atap tanah liat, tanpa harus menghindari kepala orang-orang yang tiba-tiba saja lewat.
Kemudian, begitu saja, aku menemukan Basilica de la Macarena, yang menyimpan patung The Virgin of Hope (Nuestra Señora de la Esperanza). Orang-orang lokal menyebutnya La Macarena, imaji pelindung para matador dan kesayangan kaum gipsi.
Matador kelahiran Sevilla, Joselito, menghabiskan sebagian besar harta kekayaannya untuk membelikan empat butir batu permata bagi sosok Sang Perawan yang dipahat Pedro Roldán pada abad ke-17 itu. Ketika Joselito tewas di atas ring pada tahun 1920, La Macarena—dengan lima butir air mata yang bergulir di pipinya, didandani sebagai “janda” selama sebulan.
Aku melangkahkan kaki ke dalam gereja yang gelap itu, duduk di sana, dan berdoa. Ya, aku memang bukan Katolik, tetapi bukankah—seperti Hafiz, kita percaya bahwa kita selalu bisa berdoa di mana saja? Karena bukankah Tuhan, seperti cinta, ada di mana-mana, selama kita percaya?
Dan begitulah.
Apa yang mengada di antara kita akan tetap ada, selama kita percaya. Selama hati kita berkelip dalam jeda-jeda terang-gelap, seperti kode Morse yang disampaikan lewat cahaya senter di malam hari:
.. .– .. … …. -.– — ..- .– . .-.. .-..
.- -. -.. .. .– .. … …. -.– — ..- .– . .-. . …. . .-. .
Quisiera que estuvieras aquí,
H.